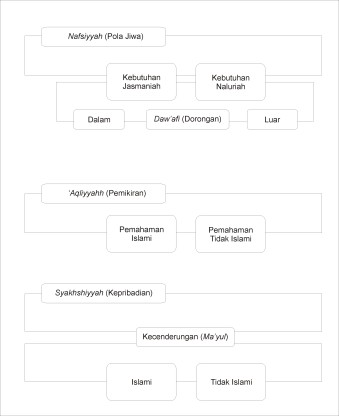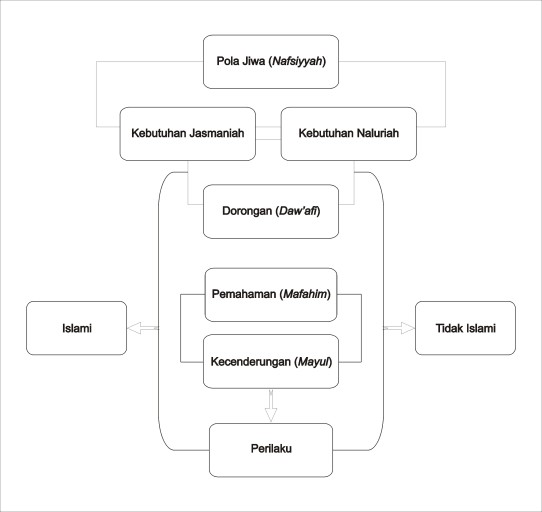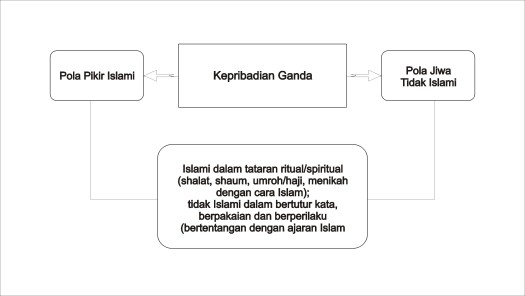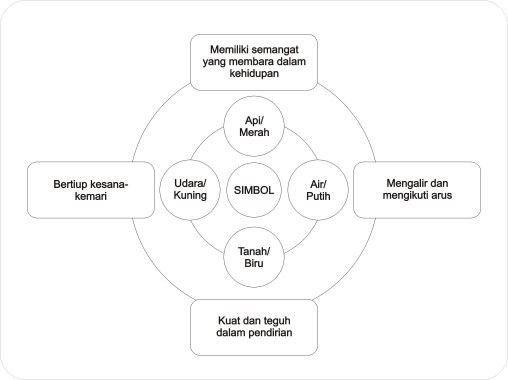Allah SWT berfirman:
[ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ [النحل: 125
Serulah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Yang Lebih Mengetahui siapa yang tersesat dari jalanNYA dan Yang Lebih Mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
(QS an-Nahl [16]: 125).
Ayat di atas menerangkan tiga metode (thariqoh) penyampaian dakwah atau pengembanan risalah. Ada cara yang berbeda untuk sasaran dakwah yang berbeda.
Pertama: dengan hikmah, maksudnya dengan dalil (burhan) atau hujjah yang jelas (qoth’i maupun zhanni) sehingga menampakkan kebenaran dan menghilangkan kesamaran. Sebagian mufassir seperti as-Suyuthi, al-Fairuzabadi, dan al-Baghawi mengartikan hikmah sebagai al-Quran. Ibnu Katsir menafsirkan hikmah sebagai apa saja yang diturunkan Allah berupa al-Kitab dan as-Sunnah.
Penafsiran tersebut tampaknya masih global. Mufassir lainnya lalu menafsirkan hikmah secara lebih rinci, yakni sebagai hujjah atau dalil. Sebagian mensyaratkan hujjah itu harus bersifat qoth’i (pasti), seperti an-Nawawi al-Jawi. Yang lainnya, seperti al-Baidhawi, tidak mengharuskan sifat qoth’i, tetapi menjelaskan karakter dalil itu, yakni kejelasan yang menghilangkan kesamaran. An-Nawawi al-Jawi menafsirkan hikmah sebagai hujjah yang qoth’i yang menghasilkan aqidah yang meyakinkan. An-Nisaburi menafsirkan hikmah sebagai hujjah yang qoth’i yang dapat menghasilkan keyakinan. Al-Baidhawi dan Al-Khazin mengartikan hikmah dengan ucapan yang tepat (al-muqalah al-muhkamah), yaitu dalil yang menjelaskan kebenaran dan menyingkirkan kesamaran (ad-dalil al-muwadhdhih li al-haq wa alimunzih li asy-syubhah). Al-Asyqar menafsirkan hikmah dengan ucapan yang tepat dan benar (al-muqalah al-muhakkamah ash-shahibah).
Pertama, Jumhur mufassir menafsirkan kata hikmah dengan hujjah atau dalil. Dari ungkapan para mufassir di atas juga dapat dimengerti, bahwa hujjah yang dimaksud adalah hujjah yang bersifat rasional (‘aqliyyah/fikriyyah), yakni hujjah yang tertuju kepada akal. Alasannya, para mufassir seperti al-Baidhawi, al-Alusi, an-Nisaburi, al-Khazin, dan an-Nawawi al-Jawi mengaitkan seruan dengan hikmah ini kepada sasarannya yang spesifik, yakni golongan yang mempunyai kemampuan berpikir sempurna. Cara dakwah dengan hikmah ini tertuju kepada mereka yang ingin mengetahui hakikat kebenaran yang sesungguhnya, yakni mereka yang memiliki kemampuan berpikir yang tinggi atau sempurna, seperti para pemikir dan cendekiawan.
Kedua, dengan maw’izhah hasanah, yaitu peringatan yang baik yang dapat menyentuk akal dan hati (perasaan). Misalnya dengan menyampaikan aspek targhib (memberi dorongan/pujian) dan tarhib (memberi peringatan/celaan) ketika menyampaikan hujjah. Sebagian mufassir menafsirkan maw’izhah hasanah (nasihat/peringatan yang baik) secara global, yaitu nasihat atau peringatan al-Quran (mawa’izh al-Quran). Demikian pendapat al-Fairuzabadi, as-Suyuthi dan al-Baghawi. Namun, as-Suyuthi dan al-Baghawi sedikit menambahkan, dapat juga maknanya adalah perkataan yang lembut (al-qawl ar-raqiq).
Merinci tafsiran global tersebut, para mufassir menjelaskan sifat maw’izhah hasanah sebagai suatu nasihat yang tertuju pada hati (perasaan), tanpa meninggalkan karakter nasihat itu yang tertuju pada akal. Sayyid Quthub menafsirkan maw’izhah hasanah sebagai nasihat yang masuk ke dalam hati dengan lembut (tadhkulu il-a al-qulub bi rifq). An-Nisaburi menafsirkan maw’izhah hasanah sebagai dalil-dalil yang memuaskan (ad-dalala’il al-iqna’iyyah), yang tersusun untuk mewujudkan pembenaran (tashdiq) berdasarkan premis-premis yang telah diterima. Al-Baidhawi dan al-Alusi menafsirkan maw’izhah hasanah sebagai seruan-seruan yang memuaskan/meyakinkan (al-khithabat al-muqni’ah) dan ungkapan-ungkapan yang bermanfaat (al-‘ibar an-nafi’ah). An-Nawawi al-Jawi menafsirkan sebagai tanda-tanda yang bersifat zhanni (al-amarat azh-zhanniyah) dan dalil-dalil yang memuaskan. Al-Khazin menafsirkan maq’izhah hasanah dengan targhib (memberi dorongan untuk menjalankan ketaatan) dan tarhib (memberikan ancaman/eringatan agar meninggalkan kemaksiatan).
Dari berbagi tafsir itu, karakter nasihat yang tergolong maw’izhah hasanah ada dua:
- Menggunakan ungkapan yang tertuju pada akal. Ini terbukti dengan ungkapan yang digunakan para mufassir, seperti an-Nisaburi, al-Baidhawi, dan al-Alusi, akni kata dala’il (bukti-bukti), muqaddimah (premis), dan khithab (seruan). Semua ini jelas berkaitan dengan fungsi akal untuk memahami.
- Menggunakan ungkapan yang tertuju pada hati/perasaan. Terbukti, para mufassir menyifati dalil itu dengan aspek kepuasan hati atau keyakinan. AN-Naisaburi, misalnya, menggunakan kata dala’il iqna’iyyah (dalil yang menimbulkan kepuasan/keyakinan). Al-Baidhawi dan al-Alusi menggunakan ungakapan al-khithabat al-muqni’ah (ungkapan-ungkapan yang memuaskan). Adanya kepuasan dan keyakinan (‘iqna) jelas tidak akan terwujud tanpa proses pembenaran dan kecondongan hati. Semua ini berkaitan dengan fungsi hati untuk meyakini atau puas terhadap sesuatu dalil. Diantara upaya untuk menyentuh perasaan adalah menyampaikan tarhib dan targhib, sebagaimana ditunjukkan oleh al-Khazin.
Cara dakwah dengan maw’izhah hasanah ini tertuju kepada masyarakat secara umum. Mereka adalah orang-orang yang taraf berpikirnya di bawah golongan yang diseru dengan hikmah, namun masih dapat berpikir dengan baik dan mempunyai fitrah dan kecenderungan yang lurus. Demikian menurut al-Baidhawi, al-Alusi, an-Nisaburi, al-Khazin dan an-Nawawi al-Jawi.
Ketiga, dengan jadal (jidal/mujadalah) billati hiya ahsan, yaitu debat yang paling baik. Dari segi cara penyampaian, erdebatan itu disampaikan dengan cara yang lunak dan lembut, bukan cara yang keras dan kasar. Dari segi topik, semata terfokus pada usaha mengungkap kebenaran, bukan untuk mengalahkan lawan debat semata atau menyerang pribadinya. Dari segi argumentasi, dijalankan dengan cara menghancurkan kebatilan dan membangun kebenaran.
Sebagian mufassir memaknai jidal billati hiya ahsan (debat yang terbaik) secara global. Al-Fairuzabadi, misalnya, menafsirkan jidal billati hiya ahsan sebagai berdebat dengan al-Quran atau dengan kalimat Laa ilaaha illa Allah. Contohnya, menurut as-Suyuthi, adalah seperti seruan kepada Allah dengan ayat-ayatNYA dan seruan pada hujjah-hujjahNYA.
Pada penafsiran yang lebih rinci akan didapati perbedaan pendapat di kalangan para mufassir. Akan tetapi, perbedaan itu sesungguhnya dapat dihimpun (jama’) dan diletakkan dalam aspeknya masing-masing. Perbedaan itu dapat dikategorikan menjadi tiga aspek:
- Dari segi cara (uslub), sebagian mufassir menafsirkan jidal billati hiya ahsan sebagai cara yang lembut (layyin) dan lunak (rifq), bukan dengan cara keras lagi kasar. Inilah penafsiran Ibn Katsir, al-Baghawi, al-Baidhawi, al-Khazin, dan M. Abdul Mun’in al-Jamal.
- Dari segi topik (fokus) debat, sebagian mufassir menjelaskan bahwa jidal billati hiya ahsan sebagai debat yang dimaksudkan semata-mata untuk mengungkap kebenaran pemikiran, bukan untuk merendahkan atau menyerang pribadi lawan debat. Sayyid Quthub menerangkan bahwa jidal billati hiya ahsan bukan dengan jalan menghinakan (tardzil)/mencela (taqbih) lawan debat, tetapi berusaha meyakinkan lawan untuk sampai pada kebenaran.
- Dari segi argumentasi, sebagian mufassir menjelaskan bahwa argumentasi dalam jidal billati hiya ahsan mempunyai dua tujuan sekaligus, yaitu untuk menghancurkan argumentasi lawan (yang batil) dan menegakkan argumentasi kita (yang haq). Imam an-Nawawi al-Jawi menjelaskan bahwa tujuan debat adalah ifhamuhum wa ilzamuhum (untuk membuat diam lawan debat dan menetapkan kebenaran pada dirinya). Imam al-Alusi mencontohkan debatnya Nabi Ibrahim a.s. dengan Raja Namrudz. Jika kita dalami, dalam debat itu ada dua hal sekaligus; menetapkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan (QS al-Baqarah [2]: 258).
Cara dakwah dengan mujadalah billati hiya ahsan ini tertuju kepada orang yang cenderung suka berdebat dan membantah, yang sudah tidak dapat lagi diseru dengan jalan hikmah dan maw’izhah hasanah.
Bagian akhir ayat memberikan arti, bahwa jika kita telah menyeru manusia dengan tiga jalan tersebut, maka urusan selanjutnya terserah Allah. Memberikan hidayah bukan kuasa manusia, melainkan kuasa Allah semata. Kita hanya berkewajiban menyampaikan (balagh); Allahlah yang akan memberikan petunjuk serta memberikan balasan, baik kepada yang menjdapat hidayah maupun yang tersesat.